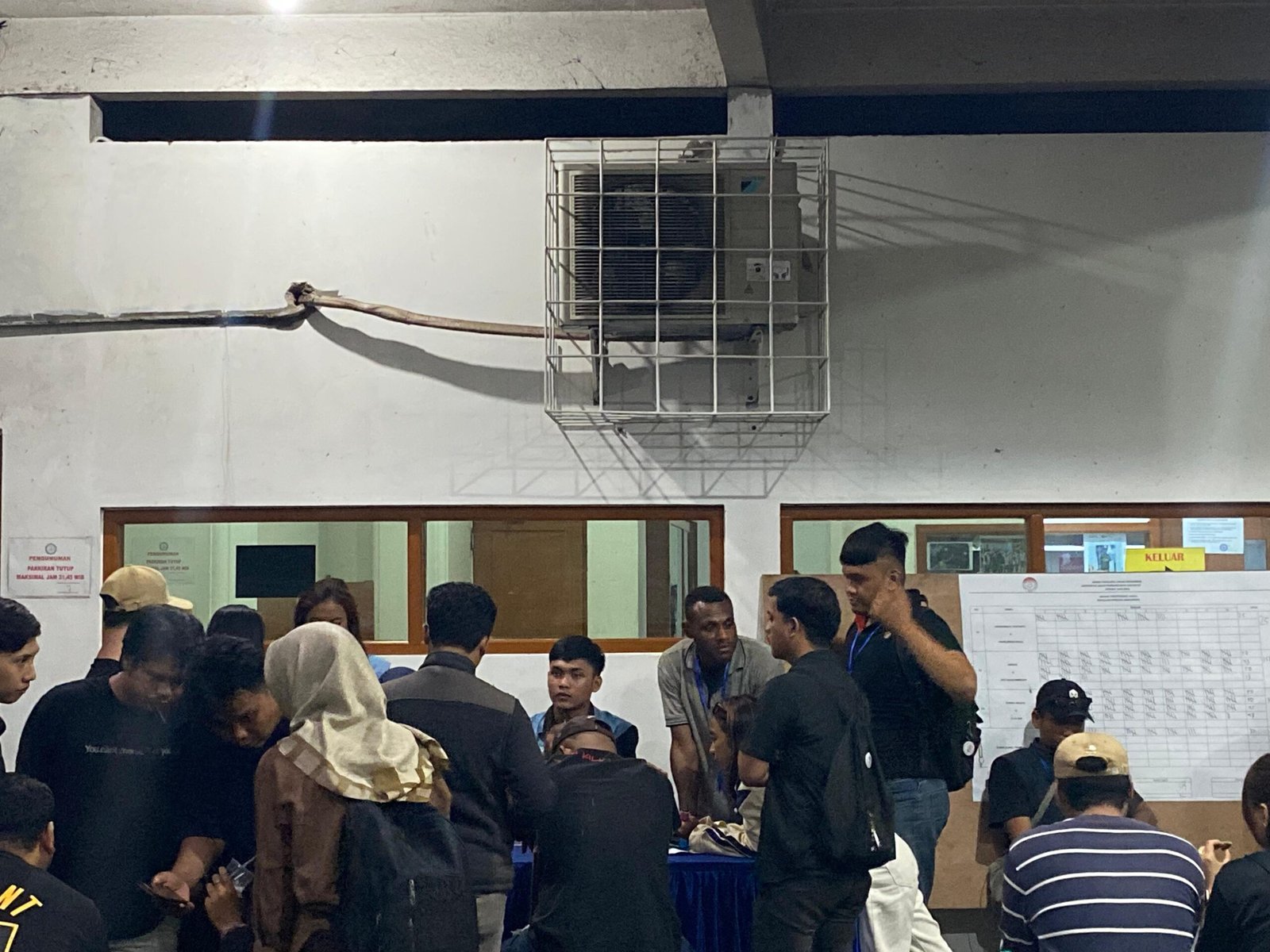Lintassuara.id – Pendidikan adalah unsur vital dalam setiap masyarakat, terutama masyarakat demokratis. Berlawanan dengan masyarakat otoriter yang berusaha menanamkan sikap menerima secara pasif, sasaran pendidikan adalah menghasilkan warga negara yang bebas, mau bertanya dan analitis dalam pandangan mereka, tapi memahami ajaran dan praktek demokrasi. Memang tidak cukup hanya mengatakan bahwa tugas pendidikan hanyalah menghindari indoktrinasi rezim otoriter dan menyediakan ajaran yang netral mengenai nilai-nilai. Itu mustahil. Tidak ada nilai-nilai yang bersifat netral, semua pendidikan menyam-paikan nilai-nilai baik itu disengaja ataupun tidak.
Peserta didik jelas diajari tentang prinsip-prinsip demokratis dalam proses pendidikan. Pada waktu yang sama, siswa didorong untuk mengemukakan pendapat, menantang pemikiran yang konvesional dengan argumentasi yang beralasan. Mungkin terjadi perdebatan, tapi buku pelajaran dalam demokrasi tidak sekedar mengabaikan fakta atau kejadian yang tidak menyenangkan atau kontroversial.
Pendidikan memainkan suatu peran penting dalam membangun masyarakat serta kesangupan masyarakat untuk menciptakan, menunjang dan meningkatkan kinerja pemerintah, sebagian besar tergantung pada ke-efektifan sistem pendidikan yang mereka lalui. Dalam demokrasi, pendidikan memungkinkan kebebasan sendiri untuk tumbuh pada waktunya. Penting untuk diperhatikan bahwa stigma pendidikan selama ini terbentuk oleh dominasi negara, tanpa kemampuan masyarakat untuk menolak. Tingginya ketakutan masyarakat ketika tidak menyekolahkan anaknya adalah salah satu stigmanya. Paradigma pendidikan ini yang kemudian menutup peluang bagi partisipasi aktif masyarakat. Mahalnya biaya pendidikan, misorientasi, tidak efektif, dan tidak efisien dalam penyelengaraannya merupakan akibat dari sentralisme tadi.
Dalam jangka pendek, desentralisasi pendidikan memang dapat menjawab beberapa problema pendidikan. Tapi untuk menjawab tantangan bangsa sangatlah sukar diatasi. Krisis kepemimpinan misalnya, pengkaderan yang dilakukan partai atau lembaga negara berpotensi menjadi solusi. Pelatihan pemimpin untuk meningkatkan politik, manajemen politik, sementara dapat menambah kaderisasi. Sebaliknya. penciptaan “ruang publik” adalah syarat utama terciptanya pendidikan partisipatif dan dialogis. Hal ini mendorong kehendak kolektif melalui perencanaan yang baik bagi semua pihak tanpa harus menimbulkan konflik.
Dalam hal ini, elite kita masih dinilai represif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan bagi berjalannya sebuah kebijakan pembangunan. Seharusnya, elite kita memandang rakyat bukan sebagai beban atau musuh tetapi sebagai aset.
Elite semestinya bisa mengajak duduk bersama rakyat dan mencari jalan keluar terbaik baik agar krisis multidimensi di negeri ini dapat teratasi. Sejauh ini misalnya, Elite kita memang belum terdengar melakukan upaya keras agar partisipasi aktif masyarakat terus terjalin.
Jika kita melihat ketegangan yang terjadi antara struktur, kemudian semakin menguatnya konflik identitas antar elite penguasa, maka ada baiknya bila kita menengok seberapa jauh peranan kaum cendekia atau cendekiawan dalam bingkai sosio politik Indonesia.
Cendikiawan adalah orang yang memposisikan dirinya untuk terlibat dalam gerak bersama dengan massa rakyat untuk pembaharuan masyarakat dengan seluruh aksi politis dan pendidikan penyadarannya. Dalam konteks historis peran cendikiawan digunakan posisinya untuk menang-gapi panggilan zaman yang berupa pendidikan, penyebarluasan ide, pembaharuan, dan kemajuan serta syarat-syarat kultural untuk tumbuh-nya pemba-ngunan di masyarakat.
Pada zaman Orba, sekelompok cendekiawan dibentuk atas restu penguasa, tentu saja berkepentingan dan digunakan posisinya untuk mendukung dan menjalankan misi dari rezim.
Kalaupun tidak, cendikiawan ini biasanya bergerak menuju cendikiawan yang bersifat elitis. Dalam kasus Indonesia. lahirnya cendikiawan lebih dibangun dari tradisi partikular yang memilih perannya untuk pemenuhan kebutuhan birokrasi pemerintah. Mereka bersikap dalam relasinya dengan negara, partai politik, univer-sitas, media massa dan pasar komersial. Dengan kata lain, cendikiawan berada dalam kondisi krisis. Budaya populer komersil itulah yang akhirnya menjauhkan fungsi cendikia sejati.
Ketika orang mengalami pendidikan dan mengolahnya pada kesadaran kritis, sebagai manusia ia menjadi sadar dan mampu memberi tanda tanya pada persoalan masyarakat. Ketika beberapa orang mengalami proses penyadaran yang sama mengelompok dan kemudian menjadi kental. Ketika massa rakyat bersatu melawan ketidakadilan, pembodohan dan kemiskinan, maka kaum cendikia-lah yang seharusnya berfungsi untuk mengembalikan akses rakyat¹o, menghancurkan hambatan kultural dan struktural yang membodohkan masyarakat.
Penulis : Abdul Hamid